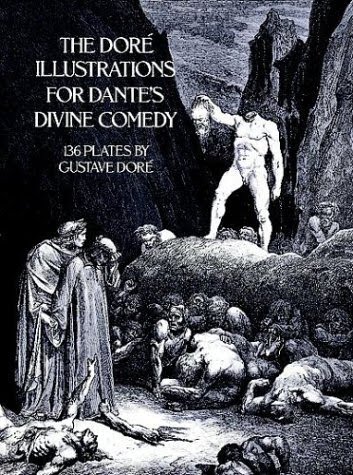katakanlah agama itu sebuah paradigma. berarti paling tidak dikenal dua konsep dalam mengembangkan dan mengkritisinya. menggunakan konsep falsifikasi Popper (Karl Popper, 1902-1994) atau konsep Kuhnian (Thomas Samuel Kuhn, 1922-1996). kita tahu bagaimana konsep falsifikasi Popper itu, paradigma yang baru muncul untuk menumbangkan paradigma lama, yang baru dianggap lebih mendekati kebenaran dibandingkan paradigma lama. sedangkan konsep Kuhnian mengatakan bahwa paradigma baru muncul setelah adanya anomali dan terjadi revolusi, paradigma lama dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan untuk sebuah masalah. dan paradigma baru dalam konsep Kuhnian tidak seperti paradigma baru dalam konsep falsifikasi Popper yang didaulat lebih benar dan dianggap mampu menjawab semua pertanyaan (sebelum muncul lagi yang baru). dalam konsep Kuhnian, paradigma baru sejajar dengan paradigma lama, walau berbeda, mereka dapat saling mengisi. saat paradigma lama mengalami kekurangan dalam memberi jawaban maka paradigma baru dapat mengisi kekurangan tersebut, begitu juga sebaliknya. tidak ada yang mendominasi sebuah kebenaran dalam konsep ini.
gunakanlah dua konsep ini dalam pemikiran agama. jika dilihat dari konsep falsifikasi Popper, maka yang akan terjadi adalah agama yang dianggap lebih benar adalah agama yang muncul belakangan. agama yang lama tumbang karena kebenaran hanyalah milik agama yang baru. maka untuk apa adanya keberagaman agama. kalau yang baru lebih baik, maka untuk apa agama yang lama bertahan? dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya hanya ada satu agama dan agama lain lebih baik ditinggalkan. dan mungkin sewaktu-waktu agama yang baru itupun harus ditinggalkan karena ditumbangkan oleh (calon) agama baru yang akan lebih baik.
lalu gunakan konsep Kuhnian. agama baru muncul untuk melengkapi agama yang lama, dan agama yang lama pun dapat melengkapi agama yang baru. kalau begitu untuk apa kita menganut satu agama? secara logika akan lebih baik kita menganut semua agama agar mencapai kesempurnaan untuk mencapai pengertian ketuhanan yang sempurna.
kedua konsep diatas memberikan satu kesimpulan "untuk apa ada agama, jika memilih satu atau banyak agama tidak dapat memberi jawaban?" kita hanya diperbolehkan memeluk satu agama dan tidak boleh tidak beragama. jika pertanyaan terus berkembang dan terus mengalahkan konsep jawaban (yang katanya merupakan produk budaya suatu masyarakat) berarti agama hanyalah sebuah produk yang sekali digunakan. bila gunanya sudah tidak ada maka harus ditingalkan dan mencari referensi dari agama lain. agama ada untuk mencapai pengertian tentang tuhan, lantas bagaimana kita dapat mencapai tuhan jika kesadaran kita tentang konsep ke-Tuhan-an terus dikoyak dan dirombak oleh konsep agama yang selama ini didaulat memberi jawaban yang memuaskan padahal pertanyaan terus muncul.
biarlah agama berkembang secra objektif dalam masyarakat, dan kepercayaan kita berkembang subjektif dalam diri dan pikiran sendiri.
Rabu, 18 Agustus 2010
Jumat, 13 Agustus 2010
Modern
Dahulu,orang-orang bisa menjadi teman dengan hubungan yang intens dan terus-menerus. Hanya mereka yang saling kenal dan tahu satu sama lain bisa mengeluarkan pernyataan "ia teman saya". Sekarang, di zaman serba modern ini, hanya dengan menekan tombol "add as friend" maka otomatis anda menjadi teman dari si A, si B dan sebagainya. Teman-teman ini jumlahnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan, saya yakin kalau jumlah orang yang benar-benar anda kenal dalam friend list situs jejaring sosial anda itu tidak sampai 50% atau mungkin tidak sampai 20%. Aneh sekali kalau kemudian keluar pernyataan dari mulut anda "ya sama kenal orang itu" jika ditanya seseorang mengenai orang lain. Saya sendiri pun jujur bahwa lebih dari separuh teman saya di situs Facebook sama sekali tidak saya kenal. Inilah hasil dari era modern, teknologi merajai, tidak perlu lagi repot karena semua serba instan dan memanjakan.
Era modern yang kini mulai usang dan membusuk bersama ideologi-ideologi mentah Hegel, Hume atau Kant mulai ditinggalkan. Produksi barang konsumsi yang menjadi ciri khas dari era industri yang mengawal era modern lewat Revolusi Prancis atau era Empirisme Inggris mulai layu dan tidak menarik. Kini orang-orang mulai beralih kepada Pascamodernisme, dengan Jean-Francois Lyotard yang dianggap sebagai salah satu konseptor awalnya. Lyotard yakin bahwa masyarakat tidak secara terus menerus dan biadab disusun berdasarkan tekonologi, namun juga lewat permainan bahasa dan diskursus, narasi-narasi menjadi penting dan tidak dapat ditinggalkan. Nampaknya poin inilah yang dilewatkan oleh pelaku Pascamodernisme kebanyakan. Entah bagaimana, teknologi dianggap mampu membebaskan umat manusia dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, yang lebih ekstrim penindasan atas manusia lain. Teknologi juga dianggap bertujuan untuk memberi tujuan bagi kehidupan sosial, jadilah kita sebuah robot dari hasil kebudayaan sendiri yang akhirnya malah tergantung padavariabel terkecil dari kebudayaan itu sendiri. Kasarnya kita ini telah menjadi budak dari kebudayaan.
Marx semasa hidupnya hanya mengenal manusia memperbudak manusia lain. Kaum Borjuis memeras kaum Proletar bagai vampir menghisap darah korbannya sampai habis denyut nadi terakhirnya. Yang dilihat Marx kala itu hanyalah komodifikasi barang yang sederhana, semisal dari bentuk balok kayu menjadi meja ukir yang kemudian terjadi alienasi antara si pengrajin dengan barang yang dihasilkannya. Sesederhana itu, bagaimana reaksi Marx jika di masa kini melihat barang yang jauh melampaui nilai gunanya? Lihatlah tas bermerk Gucci atau Louis Vuitton, harganya sungguh tidak masuk akal jika dilihat dari kegunaan barang tersebut. Alienasi semacam inilah yang kini terjadi pada dunia, hasil dari Modernitas dan percampuran dari Pascamodernime Lyotard. Dalam Modern and Self-Identity, Anthony Giddens menyatakan bahwa kita telah beralih ke Pascatradisional atau yang dikenal "Posmo". Dalam tatanan ini, individu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang untuk dapat memilihnya diperlukan kecerdasan, pertimbangan dan usahare fleksi untuk mengkonstruksi keadaan biografis hingga tercipta tatanan melalui regulasi, institusi, hukum dan tatanan moral. Sayangnya, dengan terbiasanya generasi kita dengan pop culture dan instant culture, kita menjadi tidak peduli terhadap syarat utama dalam memilih tadi. Jadilah kita apa yang disebutMarx sebagai binatang intelek, cerdas namun tidak bisa menjatuhkan pilihankarena telah terbiasa dimanja oleh teknologi hasil intelektualitas kita sendiri. Para pencipta produk kebudayaan yang akhirnya menjadi budak kebudayaanitu sendiri dan menjadi produk dari era Pascamodernisme.
Era modern yang kini mulai usang dan membusuk bersama ideologi-ideologi mentah Hegel, Hume atau Kant mulai ditinggalkan. Produksi barang konsumsi yang menjadi ciri khas dari era industri yang mengawal era modern lewat Revolusi Prancis atau era Empirisme Inggris mulai layu dan tidak menarik. Kini orang-orang mulai beralih kepada Pascamodernisme, dengan Jean-Francois Lyotard yang dianggap sebagai salah satu konseptor awalnya. Lyotard yakin bahwa masyarakat tidak secara terus menerus dan biadab disusun berdasarkan tekonologi, namun juga lewat permainan bahasa dan diskursus, narasi-narasi menjadi penting dan tidak dapat ditinggalkan. Nampaknya poin inilah yang dilewatkan oleh pelaku Pascamodernisme kebanyakan. Entah bagaimana, teknologi dianggap mampu membebaskan umat manusia dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan, yang lebih ekstrim penindasan atas manusia lain. Teknologi juga dianggap bertujuan untuk memberi tujuan bagi kehidupan sosial, jadilah kita sebuah robot dari hasil kebudayaan sendiri yang akhirnya malah tergantung padavariabel terkecil dari kebudayaan itu sendiri. Kasarnya kita ini telah menjadi budak dari kebudayaan.
Marx semasa hidupnya hanya mengenal manusia memperbudak manusia lain. Kaum Borjuis memeras kaum Proletar bagai vampir menghisap darah korbannya sampai habis denyut nadi terakhirnya. Yang dilihat Marx kala itu hanyalah komodifikasi barang yang sederhana, semisal dari bentuk balok kayu menjadi meja ukir yang kemudian terjadi alienasi antara si pengrajin dengan barang yang dihasilkannya. Sesederhana itu, bagaimana reaksi Marx jika di masa kini melihat barang yang jauh melampaui nilai gunanya? Lihatlah tas bermerk Gucci atau Louis Vuitton, harganya sungguh tidak masuk akal jika dilihat dari kegunaan barang tersebut. Alienasi semacam inilah yang kini terjadi pada dunia, hasil dari Modernitas dan percampuran dari Pascamodernime Lyotard. Dalam Modern and Self-Identity, Anthony Giddens menyatakan bahwa kita telah beralih ke Pascatradisional atau yang dikenal "Posmo". Dalam tatanan ini, individu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang untuk dapat memilihnya diperlukan kecerdasan, pertimbangan dan usahare fleksi untuk mengkonstruksi keadaan biografis hingga tercipta tatanan melalui regulasi, institusi, hukum dan tatanan moral. Sayangnya, dengan terbiasanya generasi kita dengan pop culture dan instant culture, kita menjadi tidak peduli terhadap syarat utama dalam memilih tadi. Jadilah kita apa yang disebutMarx sebagai binatang intelek, cerdas namun tidak bisa menjatuhkan pilihankarena telah terbiasa dimanja oleh teknologi hasil intelektualitas kita sendiri. Para pencipta produk kebudayaan yang akhirnya menjadi budak kebudayaanitu sendiri dan menjadi produk dari era Pascamodernisme.
Langganan:
Postingan (Atom)