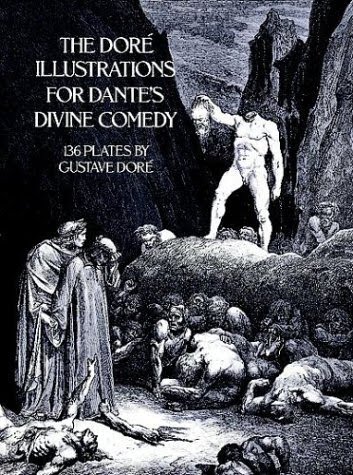Nama: I Nyoman Indra Kresna Wijaya
NPM: 0906526355
Mata Kuliah: Etnografi Indonesia
Jika kita berbicara tentang masyarakat Jawa atau orang Jawa, maka hal tersebut tidak akan lepas dari kepercayaan lokal atau kosmologi yang beredar di kalangan orang Jawa. Kosmologi-kosmologi yang secara jelas mempengaruhi bahkan menguasai sebagian besar kebudayaan Jawa, pola pikir masyarakatnya dan cara mereka bertindak. Misalnya kosmologi seputar perairan baik mulai dari bentuk sungai, danau atau yang lebih dikenal Kedhung hingga kosmologi mengenai lautan. Kita tahu kalau sebagian pola kehidupan orang Jawa dihabiskan di daerah pesisir, entah di pesisir selatan maupun utara pulau Jawa. Masing-masing wilayah ini memiliki pengetahuan lokal tersendiri yang mengajarkan bagaimana masyarakatnya memperlakukan laut, masyarakat pesisir selatan melihat laut sebagai suatu wilayah yang gaib, sakral dan harus dihormati bahkan ditakuti. Berbeda dengan pemahaman orang Jawa di bagian pesisir utara yang melihat laut sebagai wilayah yang menyenangkan, tempat mencari penghidupan dan bermain anak-anak.
Selain wilayah perairan dan pesisir, kosmologi yang beredar dan berakar kuat juga menyangkut seputar wilayah daratan dan dataran tinggi seperti bukit atau lereng gunung. Salah satu gunung yang dianggap terpenting dalam hal kosmologi dan ritual pada masyarakat Jawa adalah Gunung Merapi (2.968 mdpl, terletak di provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta), entah bagaimana Merapi telah menjadi leganda nyata dalam masyarakat Jawa apalagi jika kita melihat headline-headline surat kabar dan berita utama di media elektronik yang sedang melakukan “pengawasan” penuh terhadap Merapi karena sedang dalam masa aktif. Namun banyak warga disekitar lereng Merapi yang enggan dievakuasi karena mereka yakin Merapi tidak akan mencelakai mereka. Keyakinan tersebut sarat dengan kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya yang berada di sekitar wilayah lereng Merapi, mereka percaya bahwa Merapi memiliki nyawa sebagai penunggu, sehingga untuk menghindari kemarahan penunggunya warga perlu mengadakan ritual dan juga memberikan sesaji. Yang menarik dalam kesepakatan mengenai pengetahuan lokal ini adalah, hanya ada beberapa orang atau orang-orang terpilih yang dapat melakukan hubungan dan mengetahui kehendak dari penunggu wilayah Merapi tersebut, seperti Alm. Mbah Maridjan, jadi tidak semua orang memiliki akses istimewa ini. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan dunia gaib atau berhubungan dengan penunggu wilayah-wilayah yang disakralkan oleh masyarakat Jawa, kemudian mendapatkan tempat istimewa dan privilege dalam komunitasnya. Pengetahuan lokal tersebut menarik untuk dibahas, karena pulau Jawa, sebagai pulau terpadat di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang hampir 95% beragama Islam dan sebagaimana diketahui, agama Islam sangat melarang hal-hal yang berbau mistis dan bersifat “kepercayaan yang bercabang” antara Tuhan dan roh-roh Leluhur.
Dalam The Religion of Java, Clifford Geertz melihat kehidupan masyarakat Jawa sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaan Jawa yang akulturatif dan agamanya yang sinkretik. Geertz melihat tiga sub-kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan. Struktur-struktur tersebut adalah Abangan, Santri dan Priyayi. Geertz mendefinisikan agama sebagai suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan perasaan-perasaan (moods) dan motivasi secara kuat, menyeluruh, dan bertahan lama pada diri manusia, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai suatu hukum (order) yang berlaku umum berkenaan dengan eksistensi manusia dan menyelimuti konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura tertentu yang mencerminkan kenyataan, sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi tersenut nampaknya secara tersendiri (unik) adalah nyata ada. Dijelaskan dalam buku The Religion of Java hubungan-hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu. Sehingga, perbedaan-perbedaan yang nampak diantara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Seperti terlihat hubungan elit-elit spiritual dan rakyat biasa dalam masyarakat Jawa, sesungguhnya yang terjadi pada ksus Merapi adalah kepercayaan masyarakat yang berlebih kepada mereka-mereka yang dianggap sepuh atau sebagai juru kunci suatu tempat keramat. Hubungan yang terjadi bersifat komplementer, dimana para elit spiritual dibutuhkan sebagai orang yang mengerti dan dapat berhubungan dengan yang berkuasa atau sering disebut dalam masyarakat Jawa sebagai sing bahurekso sehingga mereka mendapat status sosial lebih tinggi dari masyarakat awam, dan tentu saja masyarakat awam juga dibutuhkan oleh para elit spritual untuk melanggengkan atau legalisasi jabatan “sepuh” tersebut.
Bicara soal kosmologi dan kepercayaan orang Jawa, maka tidak akan lepas dari yang namanya tradisi ruwatan dan slametan. Slametan kadang disebut juga dengan kenduren atau kita mengenalnya dengan kendurian, adalah sebuah upacara keagamaan paling umum dalam adat Jawa. Menurut Geertz, slametan melambangkan kesatuan misits dan sosial bagi mereka individu Jawa yang ikut serta di dalamnya. Menurut saya, hal ini adalah semaca proses untuk menyeimbangkan kosmis di lingkungan sekitar warga yang mengadakan slametan (kurang lebih sama dengan upacara adat Nalin Taun pada suku Dayak Bentian, hanya dalam skala yang lebih kecil), slametan merupakan wadah kerjasama antar-warga yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan. Tradisi slametan sendiri terbagi atas dua fungsi dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakan slametan itu sendiri. Pertama slametan desa atau bersih desa dan slametan selingan yang hanya diadakan pada saat terjadi peristiwa khusus yang tidak berulang tiap tahunnya. Dalam kasus Merapi jika kita lihat beberapa tahun belakangan, warga sekitar lereng Merapi sering melakukan upacara slametan desa dengan tujuan (menurut kepercayaan Jawa) meruwat atau menyucikan hubungan antara manusia (warga lereng) dengan ruang (wilayah Merapi), apa yang ingin dibersihkan dari desa itu tentu saja adalah roh-roh jahat yang berbahaya bagi aktivitas warga sekitar. Slametan desa ini dilakukan dengan cara memberi persembahan / aturi sesaji berupa makanan atau hidangn beserta lauk-pauknya dan hasil bumi kepada Danyang desa (roh penjaga) di tempat yang diketahui warga sebagai tempat bersemayam beliau. Desa dengan golongan Santri yang kuat, slametan desa dilakukan di mesjid dengan doa-doa Islam, sedangkan bila terjadi di desa-desa yang tidak memiliki tempat bersemayam danyang akan dilakukan di balai desa atau rumah kepala desa dan diadakan acara pertunjukan wayang kulit. Slametan tidak selalu dengan hal-hal yang penuh aroma mistik dan sakral, bagi desa dengan danyang tertentu maka akan diadakan acara hiburan dan penuh dengan rokok. Pola slametan bersih desa kadang dilakukan sebagai tindakan preventif, menolak bala, menghindari bencana alam dan sebagainya, manjur atau tidaknya para pelakunya hanya akan menganggap bahwa sesaji tidak diterima dengan baik oleh danyang atau danyang sudah terlanjur marah dan tidak dapat ditawar lagi kemarahannya. Menurut Geertz, slametan entah itu bersih desa atau selingan adalah upaya yang awalnya dirancang untuk mengintegrasikan rakyat yang kurang akrab satu sama lain. Dengan diadakannya slametan, maka warga akan terpaksa bekerjasama dan hal ini akan mengakrabkan mereka secara sadar maupun tidak. Lebih jauh tentang tradisi dalam masyarakat Jawa yang kental dengan unsur-unsur kosmologis dan kadang berlawanan dengan hukum Islam, dapat dilihat dalam The Religion of Java. Kaum abangan adalah kaum petani, sedangkan priyayi adalah kaum aristokratnya. Kaum abangan Jawa, mewakili sintese petani atas unsur yang diterimanya dari kota dan warisan kesukuan, kaum abangan Jawa adalah mereka yang melesarikan budaya kejawen (yang percaya dengan hal gaib dan mistis) berbeda dengan kaum santri yang lebih menerima hal-hal yang tertulis dalam kitab suci. Jawa sebagai suatu wilayah kultur-komplex adalah tempat berkembangnya budaya yang berorientasi terhadap sistem religi, kepercayaan dan agama yang berpusat pada konsep tentang hal yang gaib (mysterium) yang dianggap maha-dhasyat (tremendum) dan keramat (sacred) oleh manusia yang berada di dalamnya. Sifat dari hal yang gaib serta keremat tersebut adalah abadi, dahsyat, baik, adil, bijaksana, tidak terlihat dan tidak berubah, tak terbatas dan sebaginya. Intinya, sifat pada azasnya sulit dilukiskan dengan bahasa manusia, karena hal yang gaib serta keramat itu memang memiliki sifat-sifat yang sebenarnya tidak mungkin dapat dicakup oleh pikiran dan akal manusia. Kepercayaan masyarakat Jawa mengenai hal-hal gaib tidak dapat diintervensi dengan akal sehat karena hal tersebutlah yang rasional bagi mereka, saat ada beberapa warga yang menolak untuk dievakuasi dalam bencana Merapi itu karena kepercayaan mereka yang yakin bahwa Eyang Sapu Jagad (sebutan bagi masyarakat untuk Gunung Merapi) tidak akan mencelakakan keturunan beliau. Begitulah yang terjadi di tanah Jawa, itulah realitas Jawa sebagai pulau dengan ragam budayanya sendiri, berdiri diantara kosmologi dan kondisi sosial masyarakatnya.
DAFTAR PUSTAKA:
Geertz, Clifford. The Religion of Java. London: The Free Press of Glencoe. 1960.
Koentjaraningrat. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI Press. 1987.
Pamungkas, Ragil. Tradisi Ruwatan. Yogyakarta: Narasi. 2008.
Sabtu, 06 November 2010
Langganan:
Postingan (Atom)